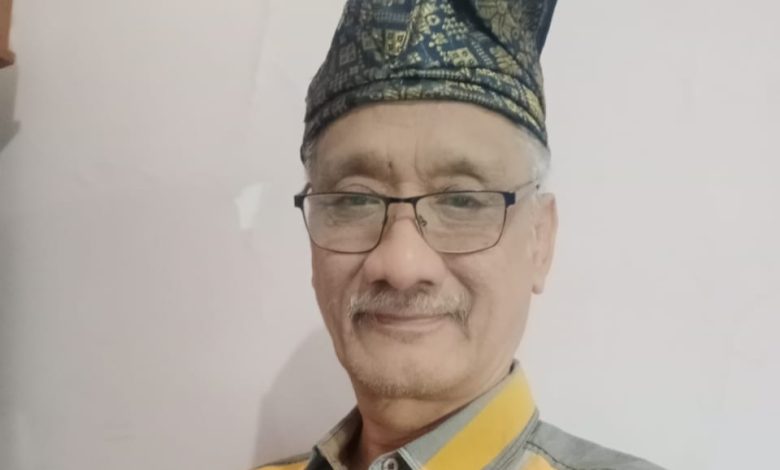
Oleh: Albar Sentosa Subari — Pengamat Hukum, Unsri
Judul tulisan ini mungkin terdengar janggal, bahkan terasa tidak masuk akal sehat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik hukum, hal seperti itu bisa saja terjadi.
Inspirasi tulisan ini datang dari sebuah kisah yang sempat ramai di media sosial. Seorang petani di pedalaman suatu daerah tiba-tiba diserang oleh harimau Sumatera. Dalam kondisi terdesak tanpa jalan keluar, ia terpaksa melawan demi menyelamatkan nyawanya. Akibat perlawanan itu, sang harimau mati. Ironisnya, petani tersebut justru dipersalahkan oleh aparat hukum dengan tuduhan menganiaya satwa dilindungi.
Pertanyaan mendasar pun muncul: benarkah perbuatan petani itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Apakah nyawa harimau lebih berharga daripada nyawa manusia?
Membela Diri dalam Perspektif KUHP
Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat konsep yang dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa (noodweer). Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum, tidak boleh dihukum.”
Menurut penafsiran R. Soesilo, pasal ini membebaskan seseorang dari hukuman jika ia terpaksa melakukan perbuatan demi melindungi dirinya. Ahli hukum Dali Mutiara menambahkan, keterpaksaan tersebut harus memenuhi syarat: ada serangan terlebih dahulu, serangan datang secara mendadak, membela diri dilakukan karena tidak ada pilihan lain, dan alat yang digunakan sebanding dengan kebutuhan.
Memang, pasal ini secara tekstual berbicara mengenai tindak pidana antar-manusia. Namun, dari sudut pandang logika hukum, situasi petani yang diserang harimau memiliki kemiripan esensial: ia melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa dari ancaman langsung.
Analogi dengan Kasus Begal
Fenomena ini bisa dianalogikan dengan kasus begal. Sering kali korban begal yang melawan justru diproses hukum, padahal ia hanya membela diri. Ada korban yang selamat, ada pula pelaku begal yang tewas. Di sinilah logika noodweer semestinya berlaku: korban tidak boleh dihukum karena perbuatannya merupakan pembelaan diri yang sah.
Begitu pula dalam kasus hewan buas. Jika terhadap sesama manusia saja pembelaan diri diakui, maka menghadapi serangan harimau seharusnya lebih layak dipandang sebagai pembelaan yang sah. Bahkan bisa digunakan metode penafsiran a contrario: bila hukum memperbolehkan melawan sesama manusia demi mempertahankan nyawa, tentu lebih diperbolehkan lagi melawan hewan buas yang nyata-nyata membahayakan.
Tanggung Jawab Pemerintah
Ada hal lain yang tak kalah penting: tanggung jawab pemerintah. Jika satwa tertentu ditetapkan sebagai satwa dilindungi, maka seharusnya pemerintah melalui dinas terkait juga memastikan hewan-hewan tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi penduduk.
Ketika seekor harimau berkeliaran hingga memasuki kawasan permukiman, itu berarti ada celah dalam pengawasan dan mitigasi konflik satwa dengan manusia. Pertanyaannya, apakah negara hanya akan melindungi hewan tanpa memikirkan keselamatan manusia yang tinggal di sekitarnya?
Seorang petani bahkan pernah berkata dengan getir: “Kalau harimau itu membunuhku, apakah pemerintah akan peduli dan memberi bantuan?” Ucapan ini menggambarkan dilema yang nyata: hukum seakan lebih berpihak pada hewan daripada manusia.
Nyawa Manusia dan Rasa Keadilan
Hukum pidana seharusnya tidak hanya dibaca dari teks, melainkan juga dari semangat keadilan. Konsep perlindungan satwa memang penting demi menjaga keseimbangan alam. Namun, prinsip keadilan menuntut agar nyawa manusia tidak diposisikan lebih rendah dari nyawa hewan.
Maka, dalam kasus seperti ini, Pasal 49 KUHP patut dipertimbangkan secara analogis. Petani yang bertindak semata-mata karena keterpaksaan tidak semestinya dikriminalisasi. Negara perlu memberi kepastian hukum bahwa membela diri dari serangan hewan buas bukanlah tindak pidana.
Kisah petani dan harimau ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai posisi manusia dan hewan dalam hukum. Perlindungan satwa tetap penting, tetapi tidak boleh melampaui logika keadilan yang menempatkan nyawa manusia sebagai prioritas.
Hukum pada akhirnya bukan sekadar pasal, melainkan juga cermin dari akal sehat dan nurani. Membela diri adalah hak dasar setiap manusia. Karena itu, tidak seharusnya seorang petani yang berjuang menyelamatkan nyawa justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan.




